Petrikor
Sore itu, hujan rintik tiba-tiba
turun. Telah lama tanah ini tidak basah oleh hujan. Meskipun karena itu aku
sempat terhenti sejenak, akhirnya aku memutuskan untuk meneruskan perjalanan.
“Aku
sudah basah oleh keringat untuk apalagi takut basah oleh sedikit hujan.”
Batinku.
Sampaiku
di sebuah warung kopi, ku buka pintunya dan lonceng berdentang, sang nenek
tersenyum selamat datang. Ku balas senyumnya dan berjalan menuju ia yang telah
menungguku.
“Apa kau tersesat menuju ke
sini?” ku dengar suaranya yang berat.
Ia tak menungguku duduk dengan
baik dulu, ia sungguh tak sabar menyampaikan kritiknya. Aku diam saja, ku
gantung tas dan jaket pada sandaran kursi lalu ku duduk, ku silangkan kakiku.
“Aku memesan minuman dulu boleh?”
Ku tatap wajah yang selalu aku cari setiap aku butuh teman bicara.
===
Secangkir kopi kampung panas, segelas es milo, dan sepiring getuk tanpa taburan kelapa tersaji di depan kami.
“Mereka memasukkan kapulaganya
terlalu banyak. Rasa kopinya jadi kurang sedap.” Setelah sedikit ngedumel,
kembali ku sesapi kopi yang masih mengepulkan asap.
“Mengapa tiba-tiba kau ingin
menikah?” Tanyanya dengan lugas.
“Kau sungguh tidak sabar, nikmati
dulu es milomu, minuman dingin membuat hatimu dingin.”
“Aku perlu menjadi bidak catur
putih, melangkah duluan. Jika aku terlena dan kau yang duluan membuka mulut,
kau pasti akan mengomentari penampilanku, kaosku yang belel, celanaku yang
dekil, sendal jepitku, bahkan kaos dalamku, segalanya yang menempel pada diriku
akan kau komentari. Aku pusing.” Jawabnya cuek.
Aku menyunggingkan senyum
menutupi hati yang tersinggung. Ia benar.
“Aku merasa perlu menikah,
petualangan yang ingin aku coba.” Aku mencoba menjawab pertanyaannya.
“Kau pikir pernikahan sesuatu
yang mudah? Hidupmu akan terikat pada komitmen dan tanggung jawab.” Jawabnya
ketus sambil mengaduk-aduk es milonya dengan sedotan.
Mendengarnya membuatku terdiam,
lalu ia pun diam, kami sibuk dengan aktivitas otak masing-masing.
“Ini roti yang baru nenek
panggang.” Suara nenek, gerakan tangan nenek menyodorkan sekeranjang roti, dan
aroma khas roti membangunkan kami.
“Nenek membuat roti karena ia
akan datang hari ini.” Ucapnya sambil tersenyum dan berlalu dari meja kami.
Warung kopi ini adalah milik
seorang pembuat roti, istrinya merupakan seorang penulis. Selain minuman dan
makanan, tempat ini dipenuhi buku, mainan tradisional, dan benda-benda kenangan
si empunya. Waktu berlalu, mereka menua, si kakek pergi dan tak kembali. Nenek
mencoba move
on dengan tidak menyajikan roti di dalam menunya, meninggalkan kue-kue
tradisional. Tapi move on tinggal
cerita, nenek gantungkan bel di pintu masuk warung ini, berharap ketika
berdentang, wajah si kakek yang muncul. Ia pun sesekali jika mood lagi bagus,
akan membuat roti yang pernah diajarkan suaminya dan membagikan secara acak
kepada pengunjung. Kebetulan hari ini rejeki kami.
===
“Aku ingin menikah bukanlah hal yang tiba-tiba, ini adalah harapan sejak lama, sejak Si masa lalu itu tak bisa kuharapkan. Setiap hari, setiap melakukan perjalanan, setiap bertemu orang, setiap duduk di cafe atau restoran, setiap ke toko buku, setiap ke taman hutan kota, ku harap bertemu jodohku, teman menuaku.”
Ku angkat kepalaku dari menatap
kopi, kuharap bertemu matanya, nihil, ia sibuk memotong-motong roti lalu
memakannya. Ku lanjutkan kalimatku.
“Bukan berarti aku menutup semua
masalah dengan menikah, bukan pula aku ingin menggantungkan hidup kepada
seseorang dengan menikah. Sesungguhnya sebesar keinginanku, sebesar itu pula
ketakutanku.”
“Kau pikir menjadi istri dan ibu
rumah tangga cocok untukmu? Kau akan kelelahan, kau akan jenuh dengan rutinitas
yang sama setiap harinya. Jika kau punya anak, kondisi akan lebih kacau lagi.”
Jawabnya enteng dengan mulut penuh roti.
“Begitukah?”
“Coba saja, kau tidak akan tau
jika tidak mencobanya.”
“Meskipun sulit aku tetap ingin
menikah." Kalimatku mantap. Ku tarik napas dan ku lanjutkan.
"Tetapi ada ketakutan yang
memenuhi kepalaku. Bagaimana jika aku menikah dengan orang yang salah, aku
belum lama mengenalnya dan tidak mengetahui tabiatnya dengan baik?” Nada
suaraku sedikit naik, tak bisa ku sembunyikan kecemasan.
“Memangnya mau mengenal dia
seperti apa?”
“Entahlah, mungkin lebih banyak
mengetahui kekurangannya, kelemahannya, profil keluarga besarnya, masa lalunya,
atau apa yang disukai dan tidak disukainya, mungkin...” Kataku dengan
menurunkan intonasi suara pada ujungnya.
Obrolan kami selingi dengan menikmati makanan dan
minuman yang di pesan, menyeruput minuman, memakan sedikit demi sedikit getuk
yang tergolek sepi.
“Mengapa pakai sendal jepit?” Aku
buka percakapan kembali. Ku lipat tanganku di meja, seperti sedang menunggu
terdakwa bicara.
“Aku hanya memakai apapun yang
nyaman, itu saja. Sudahlah, tidak perlu berpanjang pikir, aku tidak modis lah,
aku tidak menghargai orang yang ditemui, aku tidak menghargai tempat yang
dikunjungi, kenapa kita harus menghargai sebuah tempat, untuk apa?” Jawabnya
dengan intonasi yang naik turun.
Pertanyaan yang bukan diniatkan
untuk bertanya. Ia memang cenderung seenaknya. Kami diam, melihat minuman
masing-masing sambil menikmati aroma kertas pada buku tua, bau cat pada lukisan
semesta yang terpajang rapi di salah satu dinding, dan wangi bunga mawar dalam
vas di atas meja.
“Ia bisa berubah, kau pun bisa
berubah, ia berpotensi menyakitimu, kau pun berpotensi menyakitinya, mengenal
sebentar atau lama bukanlah jaminan hubungan yang langgeng. Jika kau pikir ia
setia, bisa jadi suatu hari ia berkhianat, jika kau pikir ia jujur, bisa jadi
suatu hari ia berbohong. Sebaliknya juga pada dirimu. Kita tidak pernah
benar-benar memahami seseorang, yang kita lakukan adalah melakukan penyesuaian
dan menerima ketentuan rejeki kita.” Jawabnya ringan, tanpa ekspresi tertentu.
“Tapi aku masih merasa takut.
Apakah ia seorang yang disiplin? Apakah ia rajin menyikat giginya? Apakah ia
meletakkan handuk basah di rak handuk? Apakah ia makan mengecap, tidur
mendengkur, ngences di bantal?” Ku lanjutkan obrolan kami, kini aku menjadi lebih
antusias, mumpung ada tema dan teman bicara. Bicara kepadanya seperti candu,
meskipun aku terkadang risih dengan penampilannya, tapi aku tetap memilih ia
sebagai penampung keluh kesahku.
“Bisa iya, bisa tidak. Tidak
perlu terlalu dipikirkan, kau menikah dengan manusia, bukan dengan malaikat
yang selalu benar dan bukan juga dengan setan yang selalu salah. Maklumi saja.”
“Apa nanti dia akan mendengar
pendapatku? Apa dia akan memutuskan suatu hal sendiri? Apa ia akan pergi tanpa
ijinku? Apa dia diam-diam berhutang? Apa dia memiliiki rahasia?” Aku yakin saat
ini wajahku seolah sedang menyimpan banyak kecurigaan.
“Kita cenderung akan mengandalkan
orang di samping kita untuk bercerita dan berbagi segalanya, asalkan tempat itu
nyaman. Kita juga akan sama-sama berbagi rahasia dan menyimpannya. Saling memahami
dan saling menghargai pendapat sangat penting dalam sebuah hubungan. Dan jika
sudah saling percaya komunikasi yang jujur pasti terbentuk.”
“Bagaimana jika lemari baju tidak
sempat ku rapikan? Bagaimana jika masakanku tidak enak? Bagaimana jika karena
lelah, tidak semua sudut rumah mampu aku bereskan? Bagaimana jika hal-hal kecil
itu membuat ia marah?”
“Dengan kasih sayang Allah semoga ia mengerti apa yang terjadi pada rasamu bahwa kamu pasti merasa jenuh, pada tubuhmu bahwa kamu pasti merasa letih dalam mengurus rumah dan anak-anak kelak. Aku ke toilet dulu.” Jawabnya lugas sambil meninggalkanku dengan jidat berkerut.
===
“Cobalah menikah, kalian akan belajar mencari gelombang agar bisa di frekuensi yang sama, melakukan banyak penyesuaian, belajar memperbaiki diri, dan biarkan keihklasan menguasaimu.”
Toilet membuatnya jadi lebih
bijak memilih kalimat.
“Bagaimana dengan meninggalkan
orang tua, hidup jauh dari mereka, tidak bisa setiap saat melihat mereka. Aku
sangat gugup ketika memikirkan hal ini.” Napasku tertahan, di kepalaku sudah
terbayang adegan perpisahan.
“Dalam hidup, manusia di luar
diri kita akan datang dan pergi, sudah alurnya seperti itu. Setiap orang tua
akan belajar melepas anaknya hidup bersama keluarga barunya.” Ucapnya dengan
nada rendah seolah ingin menenangkanku.
“Bagaimana rasanya memiliki
mertua, saudara ipar, bude pak de baru, nenek kakek baru, sepupu baru?
Bagaimana jika mereka tak menyukaiku? Atau bagaimana jika kami berselisih
paham?” Ucapku sambil sedikit mengembangkan tangan.
“Seperti kau menemui orang-orang
yang bersinggungan jalan denganmu saja, kau hanya perlu berbuat baik kepada
mereka, bicara saja secara normal, menjaga tata krama dan bahasa, memberikan
perhatian, menanyakan kabar, memberi makanan, ya lakukan hal yang wajar saja.
Kelak kau akan menyesuaikan diri dengan alami...”
Ku reguk tegukan terakhir kopi
kampung yang tidak lagi panas, ku tinggalkan ampasnya. Ku acungkan tangan dan
ku pesan bir pletok.
“Bagaimana jika aku merasa bosan
dengan dia?”
“Mudah-mudahan kebosanan terobati
dengan pelukan, asalkan ia bersedia memelukmu. Hehe.” Ia terkekeh, wajahnya
iseng.
“Liburan itu penting, jalan-jalanlah
ke tempat-tempat yang baru. Mengobati jenuhnya rutinitas dan menghangatkan
kembali hubungan kalian. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan
juga pasti seru. Bersenang-senanglah.” Lanjutnya dengan suara berat yang khas.
“Jika hal buruk terjadi?”
“Hidup tenang dengan pikiran
positif, baper pun ada rambu-rambu dan batasnya.”
“Bagaimana jika kami berselisih
dan berbuntut panjang, alot dan saling tidak mau mengalah?. Sebentar, aku ingin
buang air.” Lanjutku sebelum ia membuka mulut.
===
“Perselisihan ada untuk membuat kita belajar saling memahami, menguji keterampilan kita menemukan titik temu, bukan titik lemah.” Ia menghela napas.
“Ridho atas ketetapan Ilahi,
jangan sedikit-sedikit mengeluh hingga berbuntut amarah. Kuatkan diri kita, untuk
tidak terlalu sensitif terhadap aib.” Lalu ia sedot es milonya.
“Seperti kalian masing-masing
sedang memegang ujung benang, tarik-menarik pada arah yang berlawanan hanya
akan membuat tali menjadi putus.” Lanjutnya masih dengan sedotan di dalam mulutnya.
“Kenapa setiap janji temu kau
terlambat?” Ucapnya datar.
Aku tersentak, karena terlalu
fokus mendengar petuahnya.
“Mengapa ia kembali ke nol.”
Kataku dalam hati.
“Tidak tahu juga, selalu saja
begitu.” Jawabku asal sambil memalingkan wajah ke kiri dan mengosok-gosok
tengkuk dengan tangan kananku.
Dalam hati ku berkata. “Aku
selalu datang lebih dulu, tapi aku mengamatimu dari kejauhan, rasanya diriku
sangat berharga ketika ada yang menungguku, mengkhawatirkan aku, tidak sabar
ingin bertemu denganku, hehe. Meski belum tentu kau memikirkan aku selagi
menunggu.”
“Kelak aku ingin banyak melakukan
perjalanan bersama dia, bila perlu kami berjalan kaki tanpa alas kaki... kemana
saja. Aku ingin kami berbicara, berpikir, dan diam bersama sepanjang perjalanan
itu.” Ucapnya sambil menatapku.
“Kelak bersamanya pembicaraan
bukan lagi tentang diri, tapi tentang mimpi-mimpi yang akan kami wujudkan
bersama.” Lanjutnya masih dengan tatapan yang sama.
“Aku butuh ia yang membawakan
raket nyamuk untukku.” Jawabku iseng memecah keseriusan yang terasa canggung.
Kami tertawa. Terkadang terasa sangat ringan, terkadang juga terasa berat
ketika mengobrol bersamanya, terkadang sebagian kalimatnya tak mampu dicerna
otakku.
"Karena kau selalu yang
duluan digigit nyamuk ya..." Jawabnya terkekeh lalu diam.
“Jika kau telah bersama
seseorang, jangan biarkan dirimu merasa sendirian, mengejar atau mencari
sesuatu sendiri, kau akan kejauhan dan nyasar. Bicaralah pada ia yang sedang
membersamaimu.” Lirihnya, hampir-hampir tak ku dengar suaranya.
===
“Cinta? Cinta katamu, sejak kapan kau bisa mengeja cinta?” Suaranya tiba-tiba keras meremehkanku, hampir menarik seluruh perhatian pengunjung.
“Cinta memang sebuah keniscayaan,
tapi niat ketika memulai hubungan adalah hal yang penting. Tidak ada niat lain
kecuali aku ingin berpasangan dengannya di dunia dan di akhirat.” Jawabnya
tegas, sangat berbeda dari ekspresi sebelumnya.
Bir pletokku tinggal setengah, es
milonya satu kali sedot lagi tandas, getuk pun ludes, menyisakan roti yang tinggal
sepotong. Berbicara dengannya menghabiskan energi, ku pikir aku perlu memesan
kudapan lagi, tapi ia mencegahku. Sudah cukup apa yang kami makan katanya. Ku
lanjutkan obrolan kami sambil kuhabiskan roti yang tinggal sepotong.
“Mungkin aku perlu bikin
perjanjian nikah, semacam peraturan-peraturan yang harus kami taati bersama dan
visi misi kami berkeluarga. Nanti akan di evaluasi secara berkala. Kami bisa
saling bertanya, apakah tujuan kami masih sama.” Kataku datar sambil
duduk bersandar dan melipat kedua tangan di atas perut.
“Boleh juga, masing-masing
pasangan perlu mencari posisi enak mereka dalam berkomunikasi dan menjaga
ikatan mereka.” Tak kusangka ia menanggapi dengan serius. Kupikir ideku hanya
ide gila baginya.
“Bagaimana tanaman-tanamanmu?
Masih sempat kau rawat?” Tanyanya padaku.
“Sampai nanti aku mempunyai satu orang bahkan lebih yang perlu aku “rawat” pun, aku akan tetap merawat tanaman-tanamanku. Kunyit, jahe, dan kawan-kawannya sudah seperti makanan pokokku.” Jawabku dengan senyum yang mengembang, sedikit saja menyinggung tanamanku sudah membuat darahku berdesir. Jika tidak ku tahan, semua informasi mengenai khasiat bahkan nama latin dari tanamanku pasti akan meluncur dari mulutku.
“Jika kau sudah mantap ingin
menikah, ya menikah sajalah. Menikah bukan hal seram, mungkin seperti ujian
keimanan dan kesabaran dan itupun tak mungkin besar, hingga tak mampu kau
tanggung. Jangan terlalu berbenturan dengan logikalah, mainkan iman dan hatimu.”
“Hmmm....” Aku menghela napas.
Lalu menghirup habis bir pletokku.
“Aku buang air lagi ya...”Ijinku
padanya.
===
Aku kebingungan, dari depan pintu toilet aku melihat mejaku kosong, menyisakan piring dan gelas kotor, kemana ia pergi. Sesampaiku dimeja, tak kutemukan pertanda apapun, lalu aku memakai jaket dan tasku, ku putuskan untuk keluar dari warung kopi ini. Aku berjalan ke arah kasir. Sebelumnya aku lemparkan senyum kepada wanita yang seluruh lahan wajahnya dijajah oleh kerut. Sambil ku rogoh uang di dalam tas, aku bertanya kepada sang kasir.
“Mbak, seseorang yang bersama saya tadi kemana ya?” tanyaku sambil menyerahkan uang pembayaran.
“Orang yang mana ya mbak? Dari awal mbak hanya sendirian, semua sajian juga mbak habiskan sendiri, tidak ada orang lain.” Jawabnya ramah sambil tersenyum.
Setelah kutuntaskan pembayaran,
aku berjalan menuju pintu, aku linglung, heran oleh jawabannya.
“Kemana ia pergi?” Gumam hatiku.
Ku buka pintu warung kopi, ku
langkahkan kaki keluar, berdentang lonceng yang digantung tepat di atas
kepalaku, hujan rintik telah usai dan di luar, ku temukan... petrikor*.
===
*Petrikor: Aroma harum tanah
kering saat terkena hujan.
===
Terima kasih kepada handai taulan yang telah membantu terwujudnya cerita -abal-abal- ini :) Bang Top, Abi Imam, Gastem, Mbok Al, Mbakyu Nita, Bunda Rica, Bunda Putri, Lalit, Risma, Neng, Bebeb, dan Bu Asri.
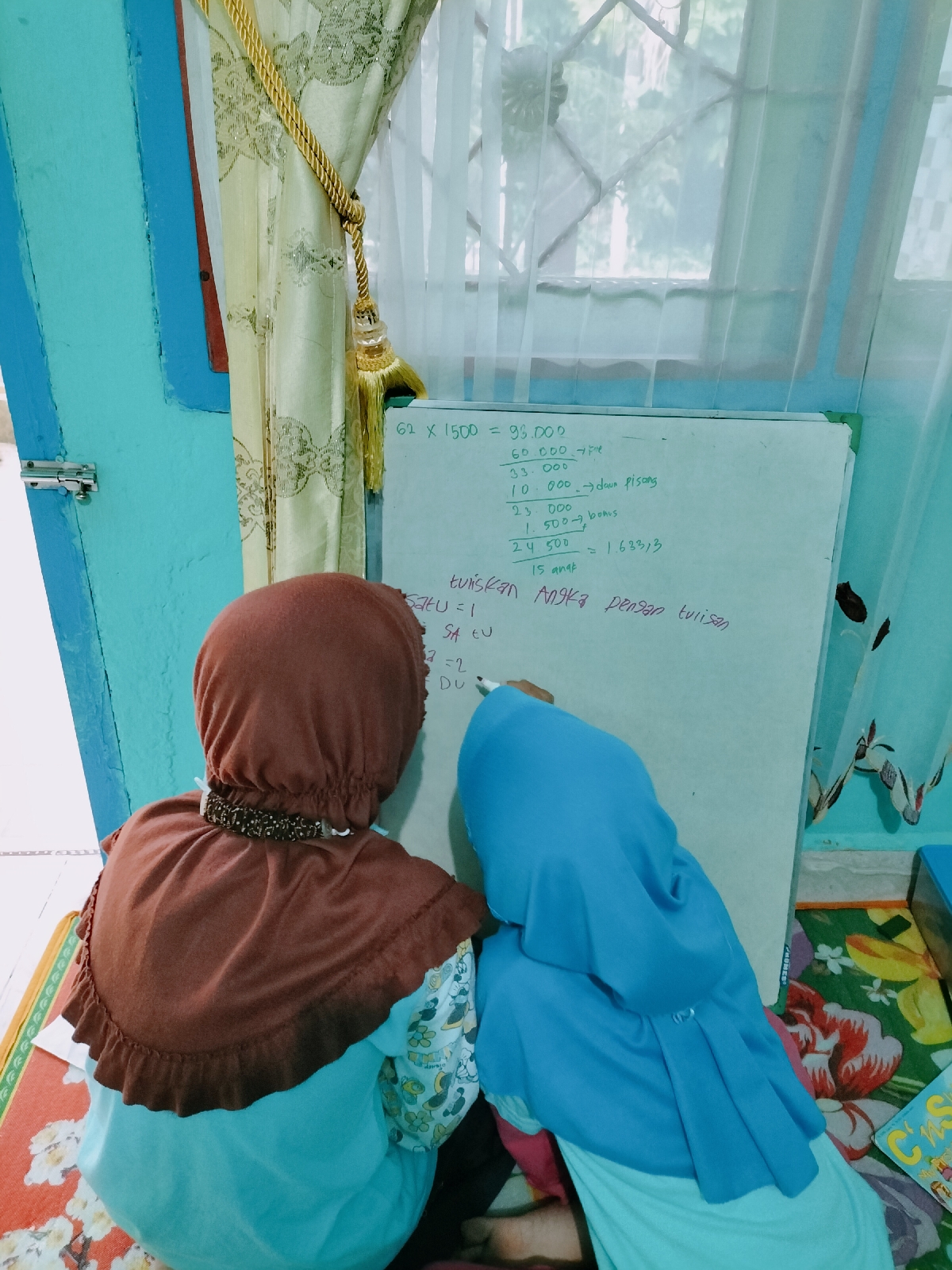

Komentar
Posting Komentar