Opia
Sore yang hangat. Toko buku itu
baru saja buka, aktivitas di dalamnya belum terlihat sibuk. Tidak ada antrean
di kasir, tiga orang penjaga toko di area masing-masing hanya menata
ulang deretan buku yang sebenarnya masih rapi. Pengunjung belum ramai hanya
terlihat tiga orang saja.
Toko ini istimewa, buka mulai
sore hari dan tutup pada dini hari. Menjadi pilihan tujuan bagi makhluk
insomnia. Bergandengan dengan toko buku terdapat kedai kopi. Sengaja dibuat
bertujuan untuk memfasilitasi pembeli yang ingin segera membaca buku yang
dibeli sambil minum kopi.
Suasana yang lengang membuatku
bisa langsung menemukannya seketika masuk ke dalam toko buku. Kerap kali aku
membuat janji temu dengannya di toko buku ini. Aroma kopi dan bau kertas menyatu
diudara yang kami hirup, alunan instrumen menyamankan telinga, kami betah
berlama-lama.
Kali ini penampilannya rapi. Alas
kakinya sneakers, atasannya kaos oblong putih polos dan jaket parka berwarna
hijau lumut dipasangkan dengan bawahan jeans berwarna
gelap. Kebetulan sekali warna jaketnya senada dengan warna overall yang
ku kenakan. Peristiwa langka.
Ku lihat ia sedang fokus dengan sebuah buku. Wajahnya serius, tangannya membolak-balik buku. Aku berjalan ke arahnya.
"Buku tentang apa?"
Sapaku padanya. Ia menoleh dan sedikit terkejut melihatku telah berdiri di
sampingnya.
"Aku belum tahu, buku ini baru
saja aku ambil dari rak. Gambar sampulnya menarik."
"Memangnya maksud gambar ini
apa, corat-coret begini." Aku melihat buku itu kebingungan mencari letak
menariknya.
"Menarik ya karena
corat-coret ini. Sesuatu yang sudah jelas gambarnya tidak menarik...
bagiku." Senyumnya mengembang, mendukung hal yang disukainya.
Ia letakkan kembali buku itu di
tempat semula dan kami mulai berjalan perlahan menelusuri rak-rak lainnya.
===
"Bagaimana kabar tanaman-tanamanmu?"
Ia memulai percakapan.
“Apakah kabar tanaman-tanamanku
lebih penting ketimbang kabarku?” Ku balas pertanyaan dengan pertanyaan.
“Mmmm...” Ia balas dengan
mengembangkan senyum.
"Baik. Aku sekarang mulai
menanam mawar, tapi hanya mawar merah. Ada dua tanaman merambat juga yang baru
aku tanam. Bunga telang dan sirih merah." Informasi kuberikan lengkap.
"Mengapa hanya mawar merah?"
"Karena warnanya mencolok,
menarik mata untuk memandang." Sambil tersenyum kuungkapkan alasanku
karena di kepalaku terbayang bunga-bunga itu sedang bermekaran.
"Untuk bunga telang dan
sirih merah dibuatkan tonggak?" Lanjutnya.
"Sementara ini merambat di
pagar."
"Hmmm..."
Kami terdiam. Tetap berjalan
perlahan. Tangan meraba-raba buku yang dipajang.
Di dalam kepalaku berputar-putar
kalimat. Bingung memilih yang cocok diucapkan untuk mulai membahasnya. Ya,
sudah tentu aku menghubunginya karena aku butuh teman bicara.
"Sepertinya bukan dia
orangnya." Ku buka suara, telapak tanganku basah karena sedikit tegang.
“Sejak kau meminta kita bertemu beberapa
waktu lalu, aku mulai menebak-nebak apa yang ingin kau katakan kali ini. Ku
pikir jalanmu menuju pernikahan akan mulus setelah bertemu dengan pujaanmu. Kau
begitu terkesan dan menyukainya. Mengapa sekarang berubah?”
“Sebenarnya aku suka mengingat kejadian
kala pertama bertemu dengannya.” Aku jadi tersenyum, ketegangan sedikit hilang.
“Malam itu aku begitu ketakutan
karena ada seorang gali* yang mencoba merampas tasku. Ketika kami
bertarik-tarikan dia datang, membantuku tepat waktu. Kami berhasil
menyingkirkan gali itu dan tasku selamat. Padahal aku tidak berdandan menarik
dan isi tasku hanya buku dan alat tulis, tidak ada barang berarti yang bisa
dijual mahal oleh gali itu. Tapi mungkin garis takdir, alasan pertemuanku
dengannya.”
“Malam itu lampu jalan membantuku
melihatnya, ia memiliki bentuk mata yang sangat aku sukai. Aku terkesan dengannya.
Lalu ia berinisiatif mengantar aku pulang, kami berjalan bersisian, mengobrol
sederhana layaknya orang-orang lain yang baru saja dipertemukan. Setelah itu
terjadi perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Aku menyukainya. Kemudian ia menjadi
pujaanku.” Kalimatku mengalir lancar.
Ia terhenti di sebuah rak buku.
Tangannya mencatut satu buku, sampulnya berwarna merah terang tanpa gambar,
hanya ada tulisan judul berfont kecil yang tercetak di sudut kanan bawah buku.
“Ini untukmu.” Ujarnya sembari
menyerahkan buku itu kepadaku. Ku terima buku dari tangannya, hanya
kulihat-lihat tanpa tertarik ingin bertanya atau membahas buku ini tentang apa.
“Kita ngobrol sambil ngopi ya.”
Sambungnya lalu berjalan ke arah kasir. Aku mengekor tanpa bersuara apapun.
===
Harum kopi menyeruak dari
gelasnya, sedangkan dari gelasku tersebar bau enak cokelat panas.
Buku yang ia belikan masih ku
pegang.
“Apa yang terjadi di antara
kalian selanjutnya?” Ia kembali memulai percakapan.
“Yang terjadi kepadaku adalah hal
klise, hubungan kami tidak direstui orang tuanya. Tapi untuk beberapa waktu
pendapat orang tuanya itu tak menyurutkan hubungan kami. Bahkan kami terus
berupaya agar bisa mengantongi restu orang tuanya.”
Ku reguk cokelat panas yang kini
sudah hangat.
“Pujaanku tetap memperlakukanku
seperti biasa, bahkan aku jadi semakin yakin dengannya, aku semakin optimis tantangan
mendapatkan restu bisa kami lewati.”
“Lalu?”
“Hari itu aku diajak untuk makan
malam bersama keluarganya. Perutku yang lapar seketika menjadi begitu sakit
sampai keringat dingin.”
“Itu artinya kau sangat lapar.”
Kalimatnya memotongku.
“Bukan.” Sahutku cepat.
“Seorang perempuan seumurku ikut
duduk bersama keluarganya. Anak teman ayahnya kata mereka. Seketika aku benar-benar
kehilangan nafsu makan, perasaanku tidak enak.”
“Lalu apa yang dilakukan
pujaanmu?”
“Pujaanku tidak berlaku apapun
pada perempuan itu, hanya sebatas sapaan dan perkenalan. Malam itu dia
mengantarku pulang, setengah jalan dia berhenti di suatu tempat makan. Katanya dia
ingin makan lagi. Aku tahu yang dia lakukan itu untuk melindungiku dari
kelaparan tengah malam. Aku hanya makan sedikit saat bersama keluarganya.” Aku
tertunduk, semua kenangan itu menggenangiku.
Kulihat ia menggerakkan tangan ke
arah pramusaji. Ia memesan nachos.
===
Sambil mengunyah nachos yang
dipesannya, ia bertanya kepadaku.
“Mengapa sekarang menanam bunga?
Bukannya kau hanya menanam bumbu dapur?” Mulutnya tetap mengunyah.
“Karena pujaanku. Ia pernah
memberiku bibit bunga mawar merah.”
“Jadi bukan karena warna bunganya
yang mencolok?”
“Alasankan boleh lebih dari satu.”
Jawabku dengan bibir tersungging.
“Oia, yang ku tanam bukan sekedar
bumbu dapur, tapi tanaman-tanaman yang juga berfungsi sebagai obat. Kamu
ingatkan waktu kakekku menderita kanker paru, meskipun kini telah tiada tapi olahan
dari tanaman-tanaman yang aku tanam cukup membantunya bertahan.”
Mengingat kakekku, kami menghela
nafas bersama.
"Aku pernah berpikir untuk
melepasnya.” Ku lanjutkan kisahku.
“Namun sikap baiknya membuat aku
ragu. Aku makin menyukainya. Hingga pikiran itu terlintas, seandainya ia
seorang yatim piatu. Huh...” Aku menutup mukaku dengan buku merah itu.
“Restu orang tua hanya awal.
Rintangan yang dihadapi kedepannya pasti akan lebih besar jika kalian tetap
berjalan bersama tanpa restu itu.” Ujarnya.
“Kamu benar, pernikahan dengan
restu orang tua saja bisa berakhir dengan perselisihan antara mertua dan
menantu. Apalagi yang tidak direstui, untuk apa hidup dalam seteru. Belum lagi
jika perselisihan melebar, hingga hubungan antar besan yang kurang baik atau
hubungan ipar yang tidak harmonis.” Jeri aku membayangkannya.
"Sesungguhnya aku
bercita-cita untuk menikah dengan seseorang yang memiliki keluarga besar. Hubunganku
dengan orang tua tidak seindah dan seideal yang aku inginkan. Mungkin keberadaan
mertua bisa memfasilitasi hasratku, aku juga tidak punya saudara kandung, bisa
menikah dengan seseorang yang memiliki keluarga besar pasti seru."
Aku hanya tersenyum, tak bisa
menanggapi pernyataannya. Dalam hati ku berkata "Semakin besar keluargamu,
semakin banyak perasaan yang mesti dijaga. Mungkin akan melelahkan."
===
"Hidup memang terlalu
kompleks." Ku pecahkan suasana yang lengang.
“Kalian cukup lama bertahan, pasti
kalian sudah membahas persoalan ini, bagaimana titik temunya?”
“Entahlah, belakangan ada sedikit
kejanggalan dari sikapnya. Setiap aku akan membahasnya dia mengalihkan
pembicaraan. Dia juga mengganti aroma parfumnya.”
“Ada korelasi dengan aroma
parfum?”
“Ya, dia cukup konsisten dengan
pilihan dalam menata diri, gaya berpakaian, gaya rambut, aroma parfum bahkan merek
pasta gigi dan sabun mandi, selalu sama. Bisa dikatakan pujaanku golongan orang
setia...” Aku tersenyum, di kepalaku terlintas harum tubuhnya.
"Sejak aku mengenalnya, dia
tak pernah mengganti parfumnya, dia bilang aroma itu sudah dia pakai sejak sekolah.
Ketika kutanyakan perihal aroma yang berubah itu, dia jawab bahwa parfum itu
pemberian temannya, dia coba pakai untuk menghargai pemberian temannya.”
Lanjutku.
“Lalu?”
“Pasti perempuan yang memberikan
parfum itu, perempuan dengan perasaan lebih dari teman. Aneh bila teman
laki-lakinya yang memberikan parfum itu. Dia pun mulai jarang menghubungiku,
sedang menghubunginya kini menjadi sulit. Jika sudah bertemu kami lebih banyak
diam, seperti kehabisan kata, hanya fokus pada aktivitas otak masing-masing. Ditambah
dengan harum tubuhnya yang berbeda, dia perlahan menjadi asing bagiku. Tapi aku
masih melekat kuat pada sosoknya.” Lagi-lagi aku tertunduk.
"Tidak kau tanyakan
bagaimana keyakinannya terhadapmu sekarang?"
"Entahlah. Aku tak bisa menanyakannya."
"Atau lihat saja matanya.
Lagi pula kamu sangat menyukai matanya, bukankah dari mata dapat ditemukan
kejujuran.”
"Rasa suka menggelapkan
objektiftas, karena terlalu menyukai matanya, aku jadi tidak pernah melihat
apapun dari sana, aku hanya menatap bentuknya, seharfiah itu matanya bagiku."
===
Hari semakin menua. Saatnya
menyudahi percakapan kali ini. Kami berdiri dan kembali berjalan bersisian, menuju
pintu keluar.
"Kau tak perlu menutupi
perasaanmu. Ungkapkan saja jika kau masih menyayanginya. Namun, jika hubungan
ini lebih baik diakhiri, ya akhiri saja. Diri dan hidupmu berharga, begitu juga
dia. Pujaanmu mungkin takut menyakitimu, hingga tak mampu menyampaikan
kata-kata dalam pikirannya.”
Mendengar perkataannya membuat
langkahku terhenti. Ia pun demikian. Tubuh kami sedikit berputar, kami
berhadapan.
"Tidak perlu dipaksakan
hal-hal yang melelahkan. Tunggu saja, nanti akan ada seseorang yang matanya tak
jemu dipandang serta balik memandangmu.” Ia katakan sambil melihat bola mataku,
membuatnya tak bisa bergerak ke kanan dan ke kiri.
"Aku ke toilet dulu."
Kalimat dan tubuhku terburu. Aku masuk lagi ke dalam bagian kedai kopi.
Ia hanya tersenyum ditempatnya
berdiri.
===
Di depan cermin besar yang
memenuhi dinding, aku melepas rintik air mata. Ia selalu begitu, berbicara pada
mataku. Ia selalu begitu, menembus dinding-dinding pertahananku. Ia selalu
begitu, opia*.
===
Setelah keluar dari toilet, ku
edarkan pandangan. Tak kutemukan lagi ia.
===
*Gali: perampok, pencuri.
*Opia: kondisi ketika menatap
mata seseorang dan mengetahui apa yang ia rasakan, apakah itu kegetiran, sedih,
takut, ataupun marah.
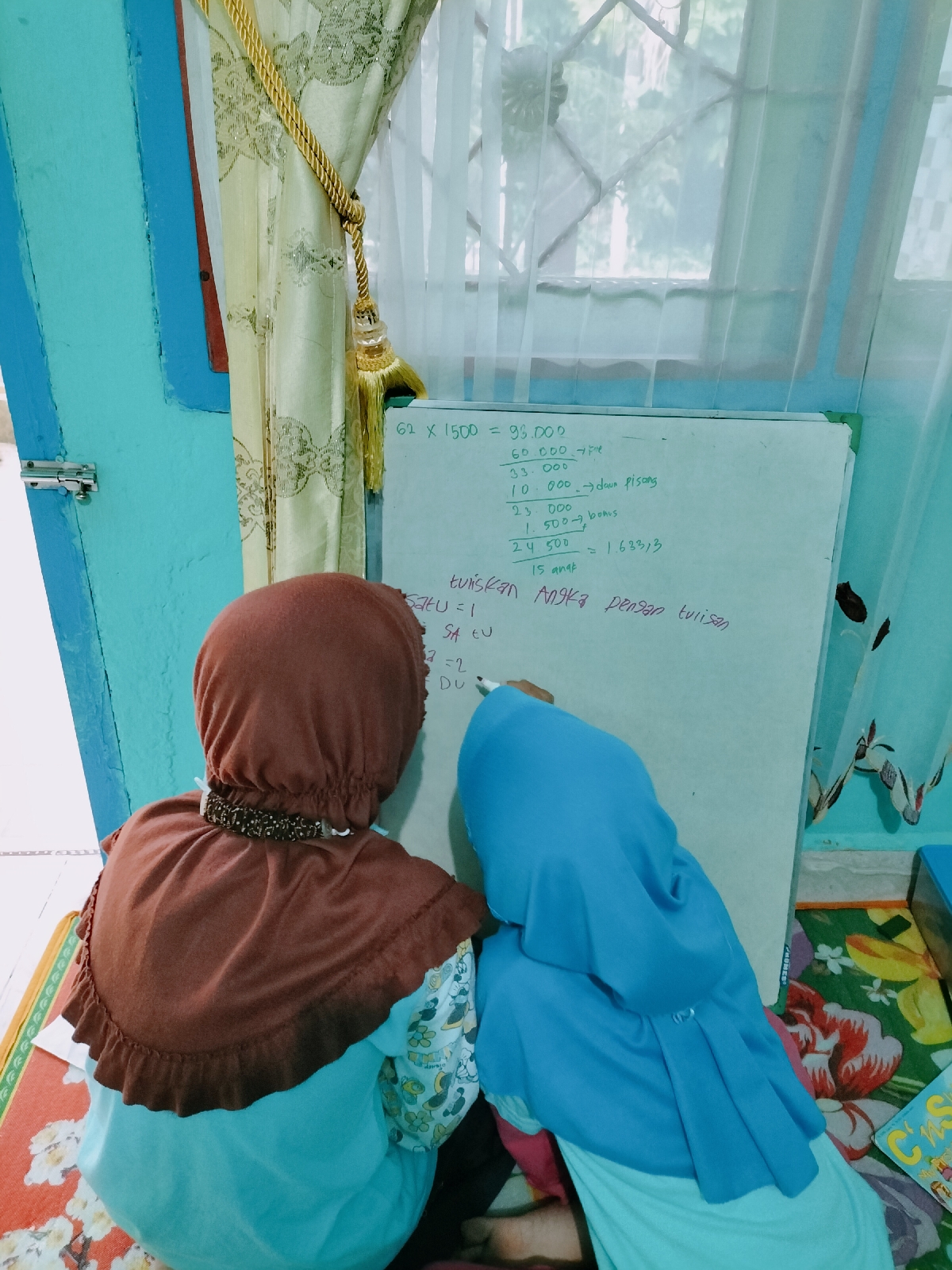

Komentar
Posting Komentar